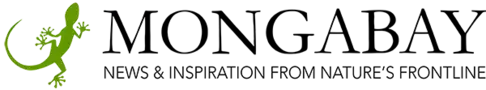Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh TEMPO.
Washington Post menyebut suku Kajang penjaga hutan terbaik di dunia. Terancam regulasi, perusahaan perkebunan, dan modernisasi.

Sinar matahari tropis menembus kanopi hutan hujan. menerangi pondok bambu di antara pepohonan hutan adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, saat pagi mulai meremang. Seorang laki-laki tua duduk bersila dengan mata terpejam, membisikkan doa-doa untuk bumi, dikelilingi sejumlah lelaki.
Setelah pemimpin spiritual (Ammatoa) itu selesai berdoa, para lelaki yang memakai sarung nila tua tersebut berdiri dan berjalan menuju hutan. Mereka membawa keranjang rotan berisi nasi, pisang, dan lilin yang dinyalakan. Ritual ini dikenal sebagai andingingi, yang diadakan setahun sekali oleh masyarakat adat Kajang. "Bumi marah kepada kita," kata Budi, anak laki-laki tak beralas kaki yang jongkok di pinggir pondok. "Itulah sebabnya cuaca makin buruk. Hujan dan banjir makin bangak. Makin panas. Kita telah berbuat dosa."
Seperti banyak bagian dunia lain, tanah mereka terkena dampak cuaca yang lebih ekstrem akibat krisis iklim. Namun, sebagaimana terlihat melalui citra satelit, hutan primer lebat milik suku Kajang bebas dari jalan dan pembangunan, menyerap hujan deras yang menghancurkan tempat-tempat lain lewat banjir bandang.
Sebagai organisasi jurnalisme nirlaba, kami mengandalkan dukungan Anda untuk mendanai liputan isu-isu yang kurang diberitakan di seluruh dunia. Berdonasi sesuai kemampuan Anda hari ini, jadilah Pulitzer Center Champion dan dapatkan manfaat eksklusif!
Saat deforestasi global berlanjut dengan laju yang mengkhawatirkan, masyarakat adat seperti suku Kajang menjadi pelindung hutan hujan dunia. Sejumlah penelitian menunjukkan, ketika memiliki hak atas tanah, komunitas-komunitas yang mengelola setengah dari total luas lahan di dunia dan 80 persen keanekaragaman hayatinya adalah penjaga yang efektif.
Budaya-budaya lokal "telah berkontribusi dalam pengurangan penghancuran hutan dengan berbagai cara", demikian kesimpulan 300-an lebih studi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2021. Suku Kajang memberikan gambaran bagaimana masyarakat adat menjalankan pekerjaan tersebut.
Komunitas itu hidup berdasarkan Pasang Ri Kajang, hukum lisan nenek moyang yang disampaikan melalui legenda dan cerita. Hukum ini bercerita tentang bagaimana manusia pertama jatuh dari langit ke hutan mereka, menjadikannya tempat tersuci di bumi.
Suku Kajang bergantung pada pertanian swasembada, tapa industri atau perdagangan yang signifikan. Di sini menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput sangat terlarang. Teknologi modern seperti mobil dan telepon seluler tidak diizinkan di wilayah tradisional. "Pohon itu seperti tubuh manusia," tutur Mail, warga Kajang berusia 28 tahun. "Jika kita menjaga hutan, kita menjaga diri kita sendiri."
Laporan 2021 Rainforest Foundation Norway, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Norwegia, menemukan bahwa dalam satu dekade terakhir masyarakat adat hanya menerima kurang dari 1 persen dana lembaga donor untuk memerangi deforestasi.
Namun kebijakan sekarang mulai berubah dengan pengakuan peran masyarakat adat dalam melindungi bumi.

Sebuah studi di jurnal ilmiah Nature Sustainability pada 2021 menemukan, di semua daerah tropis, wilayah masyarakat adat memiliki tingkat deforestasi 20 persen lebih rendah dibanding area lain. Analisis organisasi nirlaba World Resources Institute pun menunjukkan tingkat deforestasi di area masyarakat adat di Bolivia, Brasil, dan Kolombia dua-tiga kali lebih rendah daripada di luar wilayah-wilayah tersebut.
Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021, yang juga dikenal sebagai COP26, pemimpin dunia berianii mengalokasikan US$ 1,7 miliar bagi komunitas-komunitas adat dan menyebut mereka sebagai "penjaga hutan". Pelajaran tentang cara memberikan dukungan tersebut bisa dipelajari dari Indonesia, yang memiliki ribuan kelompok etnis di 125 juta hektare hutan tropisnya, hutan tropis terbesar ketiga setelah Brasil dan Kongo.
Pada Desember 2016, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui lebih dari 13 ribu hektare hutan hujan sebagai milik sembilan suku di negara ini, termasuk suku Kajang.
Pada 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan negara harus mentransfer kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat. "Itu kemenangan besar," ucap Sardi Razak, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan.
"Langkah pertama mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat."
Hingga 24 Maret 2023, pemerintah telah menetaplan 152.917 hektare hutan adat dengan peta indikatif seluas 1,2 juta hektare-hampir dua kali lipat New York, Amerika Serikat. Tahun lalu, untuk pertama kali pemerintah mengakui enam lokasi hutan adat di Papua. Seiring dengan pengakuan hutan adat, laju deforestasi hutan alam makin turun, menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Suku Kajang adalah contoh bagaimana masyarakat adat terbukti melindungi hutan di sekeliling tempat tinggal mereka. Selama bertahun-tahun mereka melindungi kekayaan satwa liar asli, termasuk rusa, monyet, babi hutan, dan burung-burung tropis, serta empat sungai yang daerah alirannya memasok air untuk beberapa desa di luar wilayah Kajang.
Dilihat dari atas, rumah-rumah suku Kajang adalah titik-titik yang tersebar di tengah hamparan hutan hujan tropis seluas 3.100 hektare. "Hutan Kajang adalah titik gelap di peta," ujar Willem van der Muur, spesialis kepemilikan tanah yang meneliti suku
Kajang. "Ini salah satu hutan hujan yang terjaga berkat hukum adat."
Wilayah Kajang terbagi menjadi 15 desa luar plus desa dalam yang membentuk wilayah suci. Filosofi suku Kajang adalah Kamase Mase, hidup dengan sederhana dan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Mereka berjalan tanpa alas kaki dan hanya mengenakan pakaian hitam atau nila tua serta menekankan kesetaraan, kerendahan hati, dan keterhubungan dengan bumi. "Kita harus menjaga tradisi," kata Jaja Tika, seorang penenun yang tidak yakin tentaig usianya tapi percaya bahwa ia setidaknya berumur 70 tahun. "Selama kita hidup, hutan akan tetap ada."
Kendali yang lebih kuat diberlakukan atas hutan Kajang, yang mencakup 75 persen wilayah adat. Sebagian besar hutan tersebut tidäk boleh digunakan, kecuali untuk kegiatan seperti melakukan ritual dan menebang kayu but membangun rumah serta pengecualian lain. Pemimpin Kajang, Ammatoa, memastikan aturan-aturan tersebut diikuti dan pelanggar akan dikenai denda atau bahkan diusir.
Suatu sore di rumah Ammatoa, seorang anggota suku Kajang diinterogasi karena menebang pohon yang ditanam ayahnya dan mencoba menjual kayunya. Pria itu duduk di atas lantai bambu di sudut ruangan, dikelilingi oleh 12 penasihat Ammatoa. "Kamu mencoba menjual warisanmu," ucap pemimpin 87 tahun itu dengan ekspresi marah melintas di waiahnya.
Dia memukul dadanya dan mengucapkan sebuah syair tradisional. "Jaga hutan," katanya. "Daun-daun pohon menciptakan hujan. Akar-akarnya menyimpan air. Jaga paru-paru bumi." Ammatoa lalu mengusir laki-laki itu. Nasibnya akan ditentukan nanti.
Sementara hukum adat bisa mencegah kelestarian hutan Kajang, ancaman serius datang dari perusahaan. Selama beberapa dekade, suku Kajang berkonflik dengan PT London Sumatra (PT Lonsum), perusahaan perkebunan karet yang memiliki area konsesi tumpang tindih dengan wilayah adat Suku Kajang.
Ketegangan mencapai puncak pada 2003, ketika 1.500 demonstran menduduki area konsesi tersebut, menyatakan bahwa PT Lonsum, yang memiliki kaitan dengan masa penjajahan Belanda, telah memperolehnya melalui pembebasan lahan ilegal. Polisi menembaki para demonstran, menewaskan empat orang dan melukai setidaknya 20 lainnya. "Itu kekerasan yang dahsyat," tutur Jumarling, seorang penjaga hutan Kajang. "Darah tertumpah saat mereka berusaha melindungi tanah kami." Sampai artikel ini selesai ditulis, PT Lonsum tidak memberikan tanggapan atas peristiwa itu.
Konflik lahan adalah hal umum di Indonesia. Menurut laporan kelompok advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria, terdapat 212 konflik agraria di 34 provinsi pada 20: pada lahan seluas lebih dari 980 ribu hektare. Karena itu, pengakuan atas hak mengelola hutan adat memberikan kekuatan legal bagi komunitas seperti Kajang.
Proses pengakuan ini melibatkan ratusan pertemuan antara pemimpin Kajang, staf pemerintah daerah, dinas kehutanan, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. "Banyak orang tidak tahu hutan mereka dimiliki pemerintah secara teknis," kata An Buyung, anggota Kajang yang menjadi Bupati Bulukumba 2014-2019. "Kini semua orang punya pemahaman lebih baik. Jika ada perusahaan yang mendekati mereka, mereka mengetahui hak mereka atas tanah."
Suku Kajang percaya mereka memiliki hampir 20.700 hektare tanah. Mereka lalu meminta pengakuan hutan adat sekitar 3.100 hektare, tapi pemerintah hanya menyetujui 310 hektare. "Ini jauh dari harapan kami," ucap Hasbi Berliani, Manajer Program Kemitraan, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam negosiasi pengakuan hutan adat Kajang.

Yuli Prasetyo, pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan pengakuan adat sedang dipercepat dengan mengubah sejumlah aturan. Namun, kendati sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi sepuluh tahun lalu, pengakuan terhadap masyarakat dan hutan adat terbentur kewajiban pengakuan dari pemerintah daerah. Menurut Van der Muur, pemerintah daerah mungkin saja tergoda memberikan konsesi wilayah adat untuk konsesi pertambangan atau perkebunan demi mendapatkan uang.
Sekarang suku Kajang menghadapi ancaman lain: modernisasi, terutama di desa-desa luar suku yang tak mengikuti Pasang Ri Kajang dengan ketat. Generasi muda yang pergi ke kota untuk belajar mulai menggunakan telepon seluler dan mengenakan pakaian produksi pabrik. Meski demikian, ada pula beberapa anak muda yang mencoba mempertahankan tradisi nenek moyang mereka.
Setelah lulus dari perguruan tinggi di Kota Makassar, Ramlah, putri Ammatoa yang berusia 38 tahun, kembali untuk membantu memimpin koperasi tenun wanita, yang menjual sarung buatan tangan di pasar lokal. Sarung, yang dipakai oleh semua warga Kajang, biasanya dibuat dengan memintal kapas yang tumbuh di lokasi setempat menjadi benang, menenunnya menjadi kain menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu lokal, lalu mewarnainya dengan daun tanaman nila yang mereka budi dayakan.
"Yang paling penting dalam hidup adalah hutan," tutur Ramlah. "Namun modernitas juga penting. Akhirnya, hukum nasional dan adat bersatu. Kita memiliki kekuatan untuk memperkuat diri sendiri."