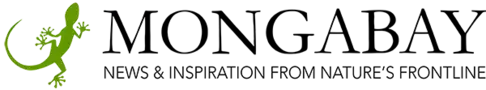Sebagian besar masyarakat yang hidup di sekitar perbukitan dan pesisir di Kepulauan Bangka Belitung, merupakan masyarakat adat. Misalnya Suku Mapur, Suku Jerieng, Suku Sawang, Suku Sekak, serta berbagai Suku Melayu lainnya. Keberadaan mereka harus diakui dan dilindungi, agar hutan dan laut di kepulauan tersebut dapat diperbaiki dan diselamatkan.
“Suku Mapur, salah satu masyarakat adat dari Suku Melayu tua di Kepulauan Bangka Belitung yang kehilangan hutannya. Banyak masyarakat adat dari Suku Melayu tua di provinsi ini yang nasibnya sama seperti Suku Mapur,” kata Jessix Amundian, Direktur Walhi [Wahana Lingkungan Hidup Indonesia] Kepulauan Bangka Belitung, akhir Februari 2022.
Misalnya Suku Jerieng yang hidup di sekitar Bukit Penyabung [300-an meter], tersebar di 13 desa; Pelangas, Kundi, Mayang, Paradong, Air Nyatoh, Berang, Rambat, Simpang Gong, Simpang Tiga, Ibul, Pangek, Bukit Terak, dan Air Menduyung [Kabupaten Bangka Barat].
Suku Maras yang hidup di sekitar Gunung Maras [705 meter], seperti di Desa Berbura dan Desa Pangkalan Niur [Kabupaten Bangka], serta berbagai Suku Melayu tua di sekitar wilayah Gunung Mangkol [300-an meter] di Kabupaten Bangka Tengah, Bukit Nenek [300-an meter] di Kabupaten Bangka Selatan, dan Gunung Tajam [510 meter] di Kabupaten Belitung.

Sementara di pesisir, selain menjadi ruang hidup sebagian Suku Mapur, seperti di Dusun Tuing dan Dusun Pejem, juga bagi Suku Sekak yang menyebar di pesisir timur, utara, selatan Pulau Bangka, dan Pulau Belitung, serta Suku Sawang di Pulau Belitung.
Ruang hidup berbagai suku atau masyarakat adat tersebut, seperti hutan, mangrove, dan laut, sebagian sudah rusak dan terancam oleh aktivitas perkebunan sawit skala besar, HTI [Hutan Tanaman Industri], penambangan timah, pertambakan udang, dan pariwisata.
Di atas daratan Kepulauan Bangka Belitung, yang hanya 1,6 juta hektar, Walhi Bangka Belitung memperkirakan luasan perkebunan sawit sekitar 273.842 hektar, HTI [275.682 hektar], penambangan timah [300 ribu hektar], pertambakan udang [2.560,7 hektar], dan belum diketahui luasan pasti infrastruktur pariwisata yang kebanyakan berada di kawasan pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil.
“Setiap bukit itu disucikan oleh semua Suku Melayu tua di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga, hutan di bukit dan kakinya menjadi wilayah hutan larangan dan hutan adat. Selama ratusan tahun mereka menjaganya,” ujar Jessix.
Begitupun pada wilayah pesisir, mangrove, dan laut, yang dijadikan wilayah adat oleh berbagai Suku Melayu tersebut.

Menyelamatkan Hutan
Sejumlah dampak positif terlihat jika pemerintah Kepulauan Bangka Belitung melindungi masyarakat adat. Pertama, hutan, sungai, mangrove dan laut, akan terus terjaga. Sebab, masyarakat adat hidupnya arif dengan alam. Kedua, menyelamatkan tradisi dan budaya yang pernah membesarkan bangsa Indonesia di masa lalu. Ketiga, sebagai sumber pengetahuan milik bangsa Indonesia yang sudah terlupakan, seperti pengobatan tradisional dan pangan [non-beras].
“Menyelamatkan masyarakat adat, seperti Suku Mapur, bukan hanya upaya mitigasi perubahan iklim dengan terjaganya hutan, mangrove, dan laut, juga menyelamatkan peradaban manusia yang selaras dengan Bumi. Menyelamatkan Bumi,” kata Jessix.
“Maka, perda [peraturan daerah] pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kepulauan Bangka Belitung mendesak untuk diwujudkan,” ujarnya.
Jessix memperkirakan, setidaknya 100 ribu hektar hutan yang dapat diberikan kepada masyarakat adat di Kepulauan Bangka Belitung. Baik yang berada di wilayah perbukitan maupun pesisir [mangrove]. Sementara lautnya sekitar 500 ribu hektar.
Dijelaskannya, saat ini tersisa 300-an ribu hektar hutan di Kepulauan Bangka Belitung, yang tersebar di 950 pulau. Mangrove tersisa, sekitar 33.224,83 hektar. Sementara laut seluas 6,5 juta hektar.
“Kami percaya jika hutan tersisa di Kepulauan Bangka Belitung dikelola masyarakat adat akan terjamin kelestariannya. Hanya masyarakat adat yang masih mampu melestarikan hutan. Begitu pun dengan lautnya.”

Arthur Muhammad Farhaby, peneliti mangrove dari Universitas Bangka Belitung menyatakan, kehadiran masyarakat adat sangat membantu upaya konservasi.
“Dari pengalaman saya meneliti kawasan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung, mangrove yang kondisinya baik, biasanya dijaga oleh tradisi dan budaya milik masyarakat adat. Hal ini bukan hanya di Pulau Bangka, juga di Pulau Belitung, serta di pulau-pulau kecil,” terangnya
Perda pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kepulauan Bangka Belitung merupakan keharusan. “Jika kita benar-benar berkomitmen menyelamatkan lingkungan di sini,” kata Arthur.
Muhammad Rizza Muftiadi, dari Simbang Institut, menjelaskan, “Masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya masih memegang adat dan tradisi, seperti melindungi hutan, sungai, mangrove dan laut. Mereka tidak tamak terhadap alam. Mereka menjaga keseimbangan.”
Lanjutnya, adanya peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, merupakan harapan sebagian besar masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, yang hidup di puluhan pulau [sekitar 50 pulau berpenghuni].
Pengakuan dan perlindungan, merupakan hak masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia. “Hak ini seperti diamanatkan Pasal 26-34 UUD [Undang-Undang Dasar] 1945,” kata Dr. Fitri Ramdhani Harahap, sosiolog dari Universitas Bangka Belitung.
Pemerintah Indonesia, kata Fitri, sebaiknya segera menggolkan RUU Masyarakat Hukum Adat, juga pemerintah di Kepulauan Bangka Belitung dapat melahirkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sudah menelurkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Misalnya di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
“Ini bentuk komitmen serius negara untuk mengakui kedudukan masyarakat adat yang sama pentingnya dengan masyarakat lainnya. Jika ini dilakukan, masyarakat adat memiliki ruang untuk mensejahterakan dirinya lewat penguasaan dan pemanfaatan tanah serta hutan adat mereka,” kata Fitri.
Selain itu, masyarakat adat memiliki kedaulatan atas identitas budayanya lewat pengakuan identitas nasional yang multikultural, serta masyarakat adat berhak untuk turut berpartisipasi lewat penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif.

Niat
Tidak mudah mewujudkan sebuah peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sebab, upaya ini akan berhadapan dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik, khususnya terkait penguasaan kekayaan alam.
“Tapi produk hukum itu kan bukan hanya bertujuan ekonomi, juga menyangkut etika atau moral guna melindungi hal-hal yang lebih penting dibandingkan ekonomi, seperti kelestarian lingkungan hidup dan kekayaan budaya dan tradisi dari sebuah bangsa,” kata Erasmus Cahyadi, Deputi Sekretaris Jenderal AMAN [Aliansi Masyarakat Adat Nusantara] Urusan Politik, awal Maret 2022.
Sangat dibutuhkan niat dari pemimpin daerah guna menyelamatkan keberadaan masyarakat adat, sebagai bagian dari sejarah hidupnya. “Menyelamatkan jejak leluhur para pemimpin dan masyarakat yang dipimpin,” kata Erasmus.
Yang harus dipahami, upaya penghilangan masyarakat adat dimulai oleh para bangsa penakluk ke Nusantara. Mereka memegang doktrin terra nullius, yang menyatakan daerah-daerah yang disinggahi para penakluk adalah tanah tak bertuan yang dapat dimiliki, sedangkan masyarakat yang lebih dulu menempatinya dinilai sebagai manusia belum beradab [Uncivilized peoples].

Di Indonesia, doktrin terra nullius terwujud dalam pemahaman bahwa masyarakat adat merupakan masyarakat tertinggal [uncivilized society] yang harus dimoderenkan. “Penyebutan orang lom atau orang belum pada Suku Mapur adalah turunan dari doktrin terra nullius tersebut,” ujar Erasmus.
Para pendiri bangsa Indonesia sangat memahami eksistensi masyarakat adat jauh sebelum berdiri Republik Indonesia. Sehingga mereka mendudukkan masyarakat adat dalam konstitusi [Undang-Undang Dasar 1945]. Yang kemudian [pasca-amandemen UUD 1945], kedudukan masyarakat adat dan hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat [2] dan Pasal 28I ayat [3] UUD 1945.
“Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi mandat pemerintah pusat tetapi juga menjadi mandat pemerintah daerah,” kata Erasmus.
Indonesia, satu dari 144 negara yang mendeklarasikan UNDRIP [United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples] yang disahkan PBB [Perserikatan Bangsa-Bangsa] di New York pada 13 September 2007.
“Prinsip-prinsip di dalam UNDRIP ini dapat menjadi dasar nilai-nilai dalam RUU Masyarakat Hukum Adat maupun peraturan daerah tentang masyarakat adat,” ujar Erasmus.

Landasan Hukum
Muhammad Syaiful Anwar, peneliti masyarakat adat dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menuturkan, “Beranjak dari kajian sejumlah pegiat masyarakat adat di Indonesia, ada sejumlah landasan hukum untuk melahirkan peraturan daerah tentang masyarakat adat.”
Pertama, Pasal 18 B ayat [6] UUD [Undang-Undang] 1945, yang isinya, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Dan, Pasal 28I ayat [3] UUD 1945; “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Kedua, sedikitnya ada 16 undang-undang di Indonesia, yang mengatur keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Mulai dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Kemudian UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; hingga UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketiga, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur masyarakat adat, misalnya TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat; Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Jadi, secara perundangan sudah cukup bagi pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung untuk melahirkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat,” kata Anwar.
Muhammad Arman, Direktur Advokasi dan Kebijakan Pengurus Besar [PB] AMAN memaparkan, “Yang paling penting, secara hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu merupakan hak, bukan pemberian pemerintah terhadap masyarakat adat. Eksistensi masyarakat adat jauh sebelum hadirnya Republik Indonesia.”
“Apalagi faktanya, hari ini masyarakat adat yang mampu mempertahankan kekayaan alam, seperti hutan dan laut, dari berbagai kerusakan. Indonesia yang berkomitmen menekan laju perubahan iklim, tentu harus berterima kasih kepada masyarakat adat. Bentuknya, ya, segera lahirkan undang-undang atau peraturan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat,” kata Arman.
Kejayaan Nusantara di masa lalu, seperti yang dikelola Kedatuan Sriwijaya, merupakan kemampuan mengoptimalkan komoditas dari masyarakat adat, tanpa melakukan penguasaan atau penghilangan eksistensi masyarakat adat.
“Yang harus dipahami, rempah-rempah yang menghidupkan perekonomian bangsa di Nusantara pada masa lalu, merupakan hasil pengetahuan masyarakat adat,” ujar Arman. [Selesai]
*Artikel ini diproduksi atas dukungan Dana Hibah Jurnalisme Hutan Hujan atau Rainforest Journalism Fund – Pulitzer Center.